Burhanuddin Muhtadi
Bagaimana seorang kandidat yang mengaku bersih dan berkomitmen pada kampanye anti-korupsi mengumpulkan suara di lingkungan di mana kebijakan moneter begitu meresap? Apakah pesan anti-korupsi cukup efektif untuk menghasilkan dukungan elektoral ketika diyakini secara luas bahwa politik transaksional adalah permainan yang paling umum, jika bukan satu-satunya, di kota? Elisabeth Kramer mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini melalui studi etnografis intensif terhadap tiga kandidat antikorupsi yang memproklamirkan diri di Indonesia. Dia memaparkan dilema yang dihadapi ketiga kandidat saat tekanan meningkat untuk menggunakan strategi pembelian suara untuk memenangkan kampanye mereka.
Seperti yang dijelaskan oleh contoh tiga studi kasus Kramer, dilema antara pragmatisme dan idealisme menyebabkan hasil pemilu yang berbeda untuk setiap kandidat. Setelah menjelaskan konteks struktural dan perubahan dalam sistem pemilu yang semakin kompetitif di Bab 1 dan masalah korupsi dan upaya antikorupsi di Bab 2, Kramer menyelami studi kasusnya. Dalam Bab 4, ia meneliti secara menyeluruh karakter Ambo, seorang calon anggota parlemen yang berkomitmen kuat pada pesan antikorupsi dan yang, meskipun mendapat tekanan kuat dari konstituen dan pendukungnya, menolak menggunakan kebijakan moneter sebagai strategi dalam kampanye pemilihannya. . Di Bab 5, ia memperkenalkan karakter Ayu, yang awalnya mengambil posisi sangat idealis dan memperjuangkan isu-isu antikorupsi dalam kampanye pemilihannya, tetapi akhirnya menyerah pada strategi pembelian suara dalam menanggapi tuntutan yang semakin pragmatis dari pemilih. Sebagai kesimpulan, Kramer menggambarkan sifat paradoks Bontor, yang rekam jejaknya dalam membela isu antikorupsi di media nasional diimbangi oleh strategi elektoral yang mempertahankan basis elektoralnya melalui pendekatan klientelis besar-besaran, yaitu pertukaran barang dan jasa untuk dukungan politik.
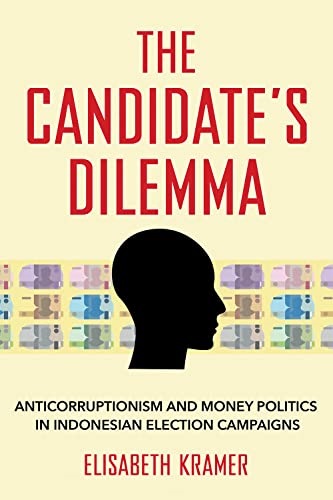
Premis dalam buku ini, yang juga menjadi dasar bagi studi kasus Kramer, adalah karena korupsi merupakan masalah utama yang sedang berlangsung di Indonesia, maka korupsi harus segera ditangani. Menganjurkan pesan antikorupsi selama musim kampanye diyakini efektif dalam mencapai perolehan elektoral yang besar. Kramer mencontohkan Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedua partai ini berkuasa atas dasar platform anti-korupsi, tetapi keduanya kemudian meledak dan kehilangan kepercayaan publik ketika elit partai mereka terlibat dalam skandal korupsi tingkat tinggi. Kramer juga mengandalkan jajak pendapat yang menyoroti korupsi sebagai sumber ketidakpuasan yang terus-menerus di Indonesia. Untuk itu, Kramer berpendapat, menjual diri sebagai kandidat antikorupsi dan menolak politik transaksional setidaknya akan menarik imajinasi pemilih.
Pada titik ini, Kramer gagal memahami, atau setidaknya tidak menguraikan, tentang keterputusan antara narasi kampanye tingkat makro atau nasional dan kampanye tingkat mikro. Sementara dia dengan tepat mengidentifikasi paradoks antara proliferasi strategi pemilu transaksional dan retorika anti-korupsi, Kramer tidak menguraikan lebih lanjut mengapa ada kesenjangan antara narasi kampanye tingkat makro dan strategi tingkat mikro. Secara makro, mobilisasi isu antikorupsi bisa bermanfaat untuk mendongkrak citra partai. Namun pada tataran mikro, pesan antikorupsi seringkali menjadi barang mewah yang tidak mampu dibeli oleh calon anggota parlemen, apalagi dijual kepada pemilih. Sistem perwakilan proporsional daftar terbuka, pertama kali diperkenalkan oleh sistem pemilu Indonesia pada tahun 2009, berarti calon harus bersaing untuk mendapatkan suara melawan lawan mereka dalam partai yang sama. Dalam sistem ini, mereka hanya perlu mengamankan sejumlah kecil suara marjinal untuk mengalahkan saingan internal mereka, dengan banyak yang terlibat dalam kebijakan moneter untuk bergerak maju. Pada pemilu 2014, ketika penulis melakukan penelitiannya, politisi sempat mempersiapkan sistem representasi proporsional daftar terbuka. Pada pemilu 2009, sistem ini diperkenalkan hanya beberapa bulan sebelum pemilu, dan masih banyak kandidat yang belum terbiasa melakukan kebijakan moneter. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika terjadi peningkatan pembelian suara 10 persen pada 2009 menjadi 33 persen pada 2014.
Perlu dicatat bahwa sementara kebijakan moneter di Indonesia relatif luas, dua pertiga dari populasi melaporkan bahwa mereka tidak tunduk pada penawaran untuk membeli suara. Kelompok pemilih ini mungkin melihat citra bersih sebuah partai sebagai alasan untuk memilih. Namun di tingkat mikro, pemilih akan kesulitan menilai apakah rekam jejak calon perseorangan benar-benar bebas korupsi atau tidak. Para kandidat juga memperebutkan 33 persen pemilih yang sudah berafiliasi dengan partai atau terhubung melalui jaringan pribadi dan bersedia memilih asalkan mendapat imbalan materi.
Seperti yang ditunjukkan Kramer, dalam sistem pemilu pertama di Indonesia, meskipun dampak pembelian suara pada pemilu kecil, strategi seperti itu dapat membuat perbedaan nyata dalam hal hasil pemilu dalam persaingan yang sangat ketat. Ketika kandidat tidak membeli suara, mereka merasa dirugikan karena pesaing mereka menggunakan teknik clientelis. Ujung-ujungnya, semua calon tergoda untuk melakukan hal yang sama, meski sadar strategi itu tidak akan mendapat banyak suara. Ini tentang margin.

Kondisi tersebut menjelaskan mengapa terdapat perbedaan antara narasi antikorupsi dari ketiga kandidat yang diulas dalam buku ini dengan strategi kampanye yang mereka terapkan dalam praktik. Bahkan calon seperti Ambo, yang menurut penulis memiliki citra antikorupsi yang lebih kuat dibandingkan Ayu dan Bontor, terpaksa melakukan kebijakan moneter tidak langsung dengan berdonasi ke masjid-masjid setempat. Sementara ia menolak untuk terlibat dalam pembelian suara massal, ia juga merasa tidak mampu mengkritik praktik kebijakan moneter di daerah pemilihannya karena khawatir hal itu akan menjadi kontraproduktif. Paradoks antara narasi tingkat makro dan strategi tingkat mikro sepenuhnya terwujud dalam kasus Bontor, yang secara heroik menyangkal korupsi di depan media nasional dan bahkan menyerukan hukuman mati bagi para koruptor, tetapi menjadi terlibat dalam praktik jual beli suara yang akut di daerah pemilihannya.
Selain pelembagaan, paradoks antara retorika antikorupsi tingkat makro dan strategi pemilu tingkat mikro juga merupakan akibat dari ambiguitas apa yang dimaksud dengan “kebijakan moneter” dalam kaitannya dengan korupsi dalam konteks Indonesia. Banyak pemilih dan politisi tidak mengartikan jual beli suara sebagai jual beli suara, melainkan memberi. Uang yang mereka terima tidak dilihat sebagai suap tetapi sebagai tanda terima kasih budaya. Perhatikan bahwa dalam kebijakan moneter Indonesia, uang umumnya didistribusikan dalam jumlah kecil. Pemilih biasa umumnya menganggap korupsi melibatkan uang dalam jumlah besar. Kurangnya kejelasan tentang pembelian suara sebagai komoditas atau hadiah ini membuat pemilih dan kandidat merasa terjebak dalam lingkaran setan praktik korupsi saat terlibat dalam pertukaran uang atau materi selama pemilu.
Sifat penelitian etnografi yang “tertanam” seperti itu berarti bahwa Kramer harus merundingkan medan etika yang sulit dalam kaitannya dengan subyeknya. Sementara dia menggunakan nama samaran untuk menyamarkan identitas ketiga kandidat yang dia pelajari, tingkat detail yang diperlukan untuk menyajikan narasinya pada akhirnya memungkinkan pembaca yang berpengetahuan untuk menebak identitas mereka yang sebenarnya. Bagi kandidat yang telah terbukti terlibat dalam kegiatan ilegal seperti kebijakan moneter, pertanyaan mungkin tetap ada tentang potensi risiko bagi mereka jika terpapar.
Secara keseluruhan, kekuatan buku ini terletak pada kemampuan penulis untuk menggambarkan secara detail nuansa kompleksitas dan kontradiksi antara retorika antikorupsi, godaan kebijakan moneter, dan kampanye pemilu. Terlepas dari keterbatasan struktural dan pragmatisme pemilih yang serupa, buku tersebut menunjukkan bahwa ketiga kandidat yang diteliti mampu memperoleh tanggapan dan hasil yang berbeda. Buku ini layak dibaca bagi siapa saja yang tertarik dengan politik Indonesia atau studi politik komparatif klientelisme.
Elizabeth Kramer, Dilema Kandidat: Anti Korupsi dan Kebijakan Moneter dalam Kampanye Pemilu IndonesiaUniversitas Cornell, Publikasi Program Asia Tenggara, 2022.
Burhanuddin Muhtadi ([email protected]) adalah Dosen Senior Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (INDICATOR) dan Peneliti Tamu di ISEAS – Yusof Ishak Institute, Singapura.
Inside Indonesia 149: Jul-Sep 2022
You may also like
-
Taman kanak-kanak di Indonesia yang terkena gempa dibuka kembali dengan bantuan dari Taiwan
-
Tingkat pengangguran di Indonesia menunjukkan kegagalan UU Cipta Kerja, kata KSPI
-
Saat Indonesia berjuang untuk mendorong melalui hukum pidana baru yang ketat, Senator Markey memimpin rekan-rekannya dalam mendesak Presiden Widodo untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi kebebasan fundamental.
-
Video menunjukkan pengungsi Afghanistan memprotes, bukan “pekerja China” di Indonesia
-
Indonesia Masih Mengingkari Kebebasan Beragama Kepada Minoritas Agama – Akademisi
